CERPEN : Encik Angka & Cik Bahasa
Assalamualaikum. Hai gaiss. Cerpen ini adalah hasil karya aku yang terbaru. Aku dah pun hantar cerpen ni kat Penulisan2u dan telah disiarkan. Kalau korang nak pi baca kat sana dan nak komen mcm2 boleh tekan link ini. :)
Selamat membaca! Andai tak best, sepuluh jari dihulur memohon ampun :) Saya masih baru dlm dunia penulisan.
__________________________
Kertas yang diserahkan Puan Waheeda sebentar tadi aku lipat perlahan. Tanpa melihat markah yang berwarna merah itu pun, sudah dapatku agak markah yang diterima. Langkah kuatur ke tempat duduk dengan wajah tertunduk. Aku yakin, semua pelajar sedang memerhatikan aku. Tidak kurang juga yang terbisik-bisik, sibuk ingin mengetahui markah ujian Matematik yang baru aku terima.
“Baiklah pelajar-pelajar semua, saya mahu awak buat pembetulan bagi semua jawapan yang salah. Pastikan kali ini awak tidak salah lagi. Saya benarkan awak semua guna kalkulator. Hantar pada Isnin minggu hadapan. Buat dalam buku Mathematics 2. Terima kasih, kelas.”
Qawiem pantas bangkit bagi memainkan peranannya sebagai seorang ketua kelas. “Alhamdulillah, terima kasih cikgu.”
Sebaik sahaja guru beranak dua itu berlalu keluar dari kelas, Ami sudah datang menyergahku. “Berapa markah kau, Ariesa?” soalnya sambil mencapai kertas ujian yang kuletak di atas meja. Aku hanya membiarkan kertas putih itu diambil. Kalau dia nak koyak pun tidak mengapa, aku redha. Aku sudah malas mahu kisahkan keputusan ujian itu.
“Riesa! For seriously, you really need to practice a lot.” Sebaris ayat itu membuatkan aku mengeluh perlahan.
“Aku tak boleh, Ami. Aku tak faham pun apa yang cikgu ajarkan dalam kelas.”
“Itu sebab kau tak minat subjek Maths! Kalau kau minat, mesti kau faham,” ujar Ami bersungguh-sungguh. Aku menggeleng laju.
“So kiranya, kau nak minat aku terhadap Maths sebesar minat aku pada subjek-subjek bahasa? Impossible, Ami Farihah. Subjek bahasa dengan subjek Matematik, jauh bezanya! Bahasa itu ibarat dia macam lautan, makin diselami makin banyak keindahan yang boleh kita jumpa. Matematik? Kalau aku selam masuk, kemudian selam naik, kemudian selam masuk lagi, boleh pengsan aku sebab migrain tahu?” Aku membebel panjang. Siap tangan terangkat-angkat lagak berdebat.
Mata bundarnya mencerlung tajam ke arahku. Mungkin geram kerana aku mengutuk subjek kegemarannya. Aku perlahan-lahan cuba untuk mengalihkan pandangan bagi mengelakkan mataku ‘buta’ akibat penangan jelingan laser itu.
“Aku ada idea!” jeritnya tiba-tiba. Alamak, dah terbuat publisiti lagi budak ini. Habis semua orang pandang. Mana tidaknya sudahlah dia menjerit sehingga kelas sebelah pun dengar, siap berdiri dengan gaya tangan diacukan ke atas pula.
“Shhh, relaks sayang oii. Apa idea kau?” Tanganku menariknya kasar, meminta gadis kecil molek itu duduk. Ami tersenyum puas lantas menunjukkan ke arah kelibat seorang pelajar tingkatan lima yang sedang berbual-bual dengan Qawiem di hadapan kelas.
Bulat mataku cuba mengenal pasti wajah itu. Sebaik sahaja reseptor mata berjaya menyalur maklumat ke otak, otak memberi arahan untuk membuat riak wajah terperanjat. Terus aku menggeleng-geleng laju lagak fleksibel sangatlah leher aku itu.
“No way man! Sampai mati pun aku takkan minta si kedekut tu ajar aku!” Suaraku yang agak nyaring menyebabkan semua orang sekali lagi terpandang ke arah kami. Qawiem yang berada di luar kelas itu juga tertoleh bagi menganalisa kekecohan yang berada di dalam ‘kawasan jajahannya’.
Nanti, kalau si Qawiem tu dengar, jadi maknanya.. Ah! Jadi maknanya si kedekut tu pun mesti dengar!
Mataku tertumpu ke arah dua tubuh di luar kelas itu. Tidak sampai dua saat, mataku teralih kembali ke atas meja yang berbalut cantik. Bimbang mataku bertambah ‘buta’ melihat jelingan berapinya!
“SIAPA yang kau maksudkan dengan si kedekut tu?” Sengaja dia bertanyakan soalan itu kepadaku sebaik sahaja aku melangkah keluar daripada blok akademik. Ketika itu, aku sengaja pulang lewat untuk mencipta skrip drama ‘Maafkan aku’ hari ini. Puas juga si Ami merasai pengalaman menjadi pengarah filem.
“Siapa? Bila aku cakap?” Aku mula menghayati watak yang telah diterangkan oleh Ami tadi. Puas kami berbincang dan merancang strategi menjawab soalan bagi setiap situasi yang dapat difikir. Penuh lima helai kertas kajang kami conteng.
Aku terus memalingkan badan, mengangkat kaki keluar dari blok akademik, bergerak ke blok asrama. Sebenarnya, sedaya mungkin aku cuba untuk mengelakkan ‘cerekarama’ ini terus berlangsung. Sudahlah aku tidak reti berlakon, kaku sahaja pergerakan aku. Tiba-tiba, bahuku seperti ditarik orang menyebabkan aku terdorong berpaling semula ke belakang. Sekelip mata, tubuhnya betul-betul berada berhadapan denganku. Ami, kenapalah kau balik dulu? Kan dah jadi macam ni.
“Apa ni, Lokman?!” ujarku sambil berundur beberapa tapak ke belakang. Sesak dadaku menahan debaran menggila. Sebelum ini, tidak pernah aku dekat dengan lelaki seperti itu.
“Berapa keputusan ujian Matematik kau?” Suara garau Lokman kedengaran setelah lama cengkerik menjadi media penghubung kami. Mendengar pertanyaannya, terus riak wajahku berubah.
“Kenapa kau nak tahu?”
“Salah ke?
Aku berpeluk tubuh tanda tidak berpuas hati. “For seriously, Lokman. Answer me.”
“Fine. Kalau kau tak nak beritahu pun, tak apa. Aku dah tahu.” ujarnya sambil mengeluarkan sesuatu daripada beg sandangnya. Bulat mata aku melihat objek tersebut. Mana dia dapat benda tu?
“Woah! Mana kau dapat benda ni?” Aku merampas kembali kertas ujian Matematik aku yang berada di tangannya. Mataku ditancapkan ke wajahnya tanda meminta penjelasan. “Well, you can ask your best friend forever to get the answer.” Terus aku teringatkan Ami yang sudah tentunya bahagia berbaring di bilik asrama. Tanpa sedar, tanganku mulai membentuk buku lima bersaiz M. Melihat reaksiku, Lokman tersengih nakal lantas membongkokkan sedikit tubuhnya yang tinggi agar sama denganku.
“Aku rasa kau perlukan pertolongan. Apa kata kalau aku jadi mentor kau?”
“Hah?” Terpinga-pinga aku mendengar tawarannya. Bukankah dia ini si kedekut? Ini tentulah termasuk dengan kedekut ilmu sekali. Kenapa dia begini?
Aku bukannya sengaja mahu memanggilnya kedekut, tapi masalahnya dia memang begitu. Sepanjang tujuh tahun dia menjadi jiran sebelah rumahku, tidak pernah dia beri aku pinjam CD game Playstation dia walaupun aku sudah hampir merayu dan melututlah bagai. Bila aku datang rumahnya untuk meminta dia ajarkan apa-apa yang aku tidak faham, terus dia bangkit, berlari pecut ke biliknya yang serba biru itu. Disebabkan itu, pada usia semuda tujuh tahun aku sudah pandai melabelkan orang. Aku patut ucapkan terima kasih kepada Lokman Hariss Abdul Latiff untuk itu.
“This offer would ends in 10 seconds. One.” Sempat pula dia bergurau senda di petang hari ini. Sengaja mahu membuatkanku resah untuk berfikir.
“Two.” Ah, bagaimana ini? Patutkah aku terima tawaran ini? Otakku masih menimbangkan tawaran yang diberikan.
“Four.” Eh, macam pelik sahaja. Kenapa dia langkau nombor tiga?
“Six.” Mataku membulat mendengar angka itu disebut. Sah, dia sengaja mahu mengusutkan fikiranku. “Hei, asal kau langkau-langkau nombor ni? Tak aci lah,” rungutku sambil menggaru kepala yang tidak gatal itu.
Dia tersengih nakal sambil menaikkan sebelah keningnya. “Eight.”
“Okay, fine. Aku terima offer kau.”
Lokman tersengih lantas mula berpaling mahu pergi. Beberapa tapak dia pergi meninggalkanku, aku bertindak untuk bersuara.
“By the way, thanks. Thanks a lot Lokman Hariss.”
“STRESSNYA jawab soalan ni!” Aku menggoncangkan botol air di hadapanku sehingga mejaku turut bergegar. Ami dan Lokman yang ada bersamaku hanya mampu menggeleng kepala.
“Relakslah, kawan. Jawab slow-slow. Betul tak Lokman?” ujar Ami cuba menyalurkan semangat. Lokman hanya mampu mengangguk kecil.
Aku sedang menghadiri kelas matematik yang dikendalikan oleh Lokman. Bagi mengelakkan sebarang gosip timbul, aku menyeret Ami untuk turut serta dalam kelas ini. Tambahan pula, Ami juga merupakan antara pelajar yang mendapat markah tertinggi ujian Matematik di dalam kelas. Hah, bagus sangatlah tu. Pelajar tercorot Matematik dikepit dua orang pelajar yang begitu profesional dalam dunia angka.
“Eleh, silibus Matematik tingkatan dua mudah sahajalah.” Riak sungguh dirinya ketika itu. Aku tahulah dia sudah tingkatan lima. Memanglah boleh kata senang. Aku ini yang sedang berada di tingkatan dua, bukannya dia!
“Berlagaklah, berlagak. Nanti Allah tarik balik nikmat kau tu, padanlah muka dengan hidung kembang-kempis tu.” Ah, sudah. Mula dah aku beri tazkirah pagi kepadanya. Dia mula menjelingku pada kadar tiga saat.
“Baiklah, Ustazah Ariesa. Ada apa-apa yang saya boleh ajarkan, ustazah?” Sengaja dia menyindirku pagi-pagi begini. Ah, geramnya aku pada dia!
Jari runcingku pantas menunjuk ke arah soalan yang sudah aku buat separuh jalan. Hakikatnya, aku siap mendapat jawapan bagi soalan tersebut tetapi apabila diperiksa pada helaian jawapan dia belakang buku, jawapannya salah pula. Sebenarnya, itulah yang membuatkan aku jadi tertekan dengan Matematik. Penat-penat buat formula itu ini, tup-tup salah pula jawapannya.
Lokman merenung buku latihanku seketika lantas mula menerangkan segala bagai formula yang dia tahu. Satu persatu dia tunjukkan di atas kertas conteng.
Aku mengambil peluang untuk menilik wajahnya dengan lebih dekat. Oh, beginikah wajah lelaki terhangat di pasaran asrama puteri sekolah? Benarlah aku buta. Selama ini, aku asyik berkata kepada peminat-peminatnya yang ramai bahawa dia langsung tidak mempunyai rupa. Sekarang rasanya, aku terpaksa menelan kata-kataku sendiri.
Kulitnya kuning langsat, tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap. Hidungnya mancung, mungkin kerana mengikut genetik keluarga. Dalam pada itu, aku cuba untuk mencari kekurangan Lokman. Namun, hampa. Segala-galanya kelihatan sempurna sekali di wajahnya. Apa yang mahalnya pada dirinya adalah sepasang mata yang mempunyai pandangan yang begitu redup. Sekali dia merenung, terasa damai hati kerana matanya terlalu indah.
“Woi! Kau dengar tak apa yang aku terangkan tadi?” Jeritannya menyebabkan khayalanku mati serta merta. Terus aku tertoleh ke kiri dan ke kanan mencari kelibat seseorang.
“Ami mana?” Ish, takkan dah balik kut. Beg dia pun sudah tiada ini.
“Ah, tak payah tukar topik! Jawab soalan aku tadi!” Aku rasa seperti ingin mencari penyumbat telinga sekarang. Dia ini tertelan mikrofon ke tadi?
“Dengarlah..” ujarku lembut. Hakikatnya, aku langsung tidak ingat walau satu formula pun yang diterangkannya sebentar tadi.
“Oh, okay. Now, I want you to explain this question to me. Use the formula that I told you just now. Could you?” ujarnya panjang, sedikit memaksa. Ah, sudah. I’m dead. Seriously.
Mata redupnya terus- menerus menjeling aku. Malah, dia sudah berpeluk tubuh sambil menanti aku untuk bersuara.
“Lokman..”
“Hmmm.” Dia membalas dengan nada yang cukup dingin. Ah, aku perlu buat sesuatu ini.
“Sebenarnya… orang tak dengar pun apa yang Lokman cakap tadi. Sorry…” Aku menuturkan ayat tersebut setelah lama berdiam diri. Puas aku cuba untuk merangka ayat untuk menerangkan situasi sebenar. Tup-tup, terkeluar pula penggunaan kata nama ‘orang’ dan ‘Lokman’. Aduh, malunya.
Selesai sahaja aku menuturkan kata, terus aku tertunduk cuba menyembunyikan pipi yang merah. Sebenarnya, ia juga taktik untuk aku cuba menahan segala lava kemarahan yang bakal dia pancurkan.
Tanpa melihat, aku mendengar dia melepaskan nafas kasar. Dengan lembut dia berkata, “Tak apalah, biar aku terangkan semula. Dengar baik-baik.”
Mendengar kata-katanya, terdongak aku merenung wajahnya lama. Dahiku dikerutkan tanda tidak berpuas hati. “Macam tu saja?”
“What?
“No, maksud aku, macam tu saja? Kau tak marah aku, membebel or what so ever that had you did before? For seriously?”
“Perlu ke aku buat semua tu?”
“Tak, maksud aku…” “Dahlah, aku penat ni. Cepat dengar, aku nak terangkan semula. Dengar baik-baik.” Lokman pantas memotong kata-kataku. Melalui corong matanya, ada satu rasa yang sebelum ini tidak pernah aku lihat selama aku menjadi menteenya.
Benar kata orang, mulut mungkin boleh menipu, tapi mata takkan boleh menipu pandangan orang.
“RIESA!” Langkahku terhenti saat suara garau itu memanggilku. Saat aku menoleh ke belakang, tubuh tinggi Lokman datang menghampiriku.
“Malam ni, kau ada kelas.” Kata-katanya menyebabkan aku hampir tersedak gula-gula FruitPlus aku kunyah dari tadi. “What? I thought the next class would held on Saturday. Macam biasalah kan? Kenapa buat kelas tiba-tiba ni?”
Dalam diam, aku memuji kesegakannya hari ini. Dengan baju pengawas biru yang dilipat lengannya sehinga ke paras siku, membuatkan dia nampak segak dan cool.
“Aku dah tahu markah ujian Matematik kau baru-baru ni.” Gulp! Terperanjat punya pasal, aku sudah tertelan gula-gula tadi. Nasib baik tidak tercekik.
“Teruk tahu tak? Cukup-cukup makan sahaja markah kau. Ini pun nasib baik lulus. Kurang saja satu markah, kau dah gagal tahu?!”
“Tahu..” Aku sudah mula menundukkan wajah. Tiba-tiba hati ini dipagut rasa sayu. Mungkin, sekali lagi dia mengherdikku, menitislah air mataku.
“Dah, malam ni after solat isyak dekat pusat sumber. Bawa sekali kertas ujian kau yang teruk tu!” Lokman mengherdik sekali lagi lantas berpaling ingin berlalu pergi. Tanpa sedar, air mataku mula mengalir dan esakan halus mula kedengaran. Tanganku meraup wajah yang sudah dibasahi air mata itu.
Entah mengapa, tiba-tiba hari ini aku beremosional pula. Biasanya, aku tidak seperti ini. Pantang diherdik, tentu aku melawan kembali.
“Hei, janganlah menangis..” ujarnya lembut. Eh? Dia patah balik? Tangannya cuba untuk menarik lenganku yang berlapik dengan baju sekolah. Namun, usahanya ternyata tidak berjaya. Aku sedaya upaya cuba untuk mengeraskan tanganku.
“Aku tak bermaksud untuk buat kau menangis..” pujuknya lembut. Dari celahan jariku, aku dapat melihat dia berdiri beberapa tapak daripada diriku, kelihatan kekok sekali. Itulah, berlagak lagi. Bila perempuan menangis, tidak tahu hendak berbuat apa.
Setelah puas berdiri di situ, aku mengambil keputusan untuk kembali ke kelas setelah terdengar deringan bunyi loceng menandakan waktu rehat kedua sudah pun tamat. Sengaja aku membiarkan dia terpinga-pinga seorang diri di hadapan koperasi sekolah.
“Ariesa, aku minta maaf! Aku tak bermaksud…” jerit Lokman tatkala aku berlalu meninggalkannya.
BOLEH tahan lama juga aku habiskan masa di dalam tandas perempuan di aras dua blok akademik sekolah. Aku ini jenisnya bila sudah menangis, susah untuk berhenti. Selepas puas menangis, aku pula sedaya upaya cuba untuk menghilangkan petanda-petanda di wajah bahawa aku baru sahaja selesai menangis. Mujurlah waktu selepas rehat kedua tiada guru yang akan masuk ke dalam kelasku kerana semua guru perlu menghadiri mesyuarat bersama pengetua.
Sebaik sahaja kakiku melangkah masuk ke dalam kelas, Ami berlari terus untuk mendapatkanku. “Riesa! Kau menangis ke?” Aku membalas pertanyaannya dengan senyuman lemah. Alamak, buang masa saja aku basuh muka tadi. Si Ami ini tetap juga perasan.
Setelah aku melabuhkan punggung di atas kerusi kayu, terus Ami menghulurkan sepucuk surat yang berlipat. Aku menyambut surat itu dengan pandangan pelik. “Apa ni?”
“Aku rasa kau patut baca sekarang, sayang,” ujar Ami sedikit serius. Ah, bertambah bingung aku dengan perangai Ami sekarang. Sekejap serius, sekejap main-main. Perlahan-lahan aku membuka kertas kajang berlipat itu. Melihat bait-bait kata yang tertulis diatas kertas, aku sudah dapat meneka siapa pengirimnya.
Lama sangatkah aku bertapa di tandas itu sehingga lelaki itu sempat mengarang surat buatku? Membaca surat tersebut, membuatkanku rasa keliru sehingga aku mengulang bacanya berkali-kali.
Assalamualaikum Ariesa Adryana,
Bagaimana dengan kau sekarang? Aku harap emosi kau dalam keadaan stabil sekarang. For seriously, emosi aku tadi tidak menentu tadi. Aku cuma rasa menyesal sebab aku banyak main-main selama aku mengajar kau. Sampai keputusan kau begitu teruk macam tu, aku rasa akulah penyebab keputusan peperiksaan kau teruk begitu.
For your information, aku langsung tak bermaksud untuk buat kau menangis. Dan sebenarnya, aku tak sangka mulut aku boleh celupar sehingga begitu sekali. Mungkin kerana terlalu tertekan, sebab aku baru sahaja baru lepas kena bebel dengan cikgu sebab aku tak siapkan modul yang dia bagi. Tak pasal kau pula jadi tempat melampiaskan kemarahan aku.
Kau tahukan, tahun ini aku hendak SPM. So, sepatutnya aku kinda busy, ikut logik akal mesti tak sempat nak ajar sesiapa pun. Mesti kau tertanya-tanya, kenapa agaknya aku sanggup ajar kau? Sebenarnya, aku rasa aku perlu berbuat sesuatu kepada seseorang yang tidak pernah aku buat baik dengannya. Lagipun dahulu semasa kau darjah satu, aku asyik sombong dengan kau. Sebab tu, aku rasa aku perlu buat sesuatu untuk menghilangkan dendam yang membara dalam hati.
Jadi, bila Ami beritahu aku yang keputusan Matematik kau teruk, aku terus buat keputusan untuk menjadi mentor kau. Kalaulah kau tak terima offer aku masa tu, aku rasa aku mungkin akan gagal dalam SPM nanti sebab tak dapat restu kau.
Ariesa, aku minta maaf sangat sebab tak dapat nak pujuk kau. Sorry, fikiran aku betul-betul buntu tadi. Tambahan pula, aku bukanlah jenis yang senang rapat dengan perempuan. Aku rasa nak cekik diri aku sendiri sebab buat perempuan yang begitu penting buat diri ini menangis. Wallahi.
Yang ikhlas,
Lokman Hariss.
Setelah aku mengulang baca surat itu sebanyak tiga kali, mataku terkelip-kelip sendiri. Tidak percaya bahawa yang menulis surat ini adalah pelajar lelaki yang nakal bernama Lokman Hariss. Lebih-lebih lagi pada bahagian di penghujung surat itu. Aku begitu ragu sekali sehingga aku tidak sedar bahawa aku sudah membaca bahagian tersebut hampir enam kali.
‘Aku rasa nak cekik leher aku sendiri sebab buat perempuan yang begitu penting buat diri ini menangis.’
Apa semua ni, Lokman? Janganlah buat aku buntu…
MALAM itu, aku rasa seperti ingin ponteng sahaja prep malam. Tetapi, memikirkan perkara yang berlaku petang tadi, menggagahkan diri aku untuk hadir ke kelasnya malam itu.
Aku harap dia boleh beri sedikit penerangan tentang hal itu.
Suasana sepi di dalam pusat sumber berhawa dingin itu ditambahkan lagi dengan perang dingin antara mentor dan menteenya. Malas-malas aku mendengar penerangan daripada Lokman. Apabila disuruh mengulang, aku cuba untuk menerapkan rasa bersungguh-sungguh dalam diri namun ego lebih menguasai diri.
Sekumpulan pelajar puteri yang ada di dalam pusat sumber itu kelihatannya berbisik-bisik melihat aku bersama jejaka idaman mereka. Cemburu ke? Mereka ingat aku nak sangatlah duduk dengan dia ni? Ambillah Lokman korang ni!
Beberapa ketika dia menanti aku membuat latihan, keluhan demi keluhan terbit dari bibirnya. Tanganku yang ligat menconteng pelbagai abstrak di atas kertas garis satu itu terhenti seketika.
“Could you just forget what happened last evening and focus to what we’re learning now?”
Aku menjelingnya pada kadar tiga saat lalu membalas dengan dingin. “No.”
“Ariesa, apa yang kau nak aku buat? Aku sanggup buat apa-apa saja. Serious talk.” Lokman berkata, sedikit merayu. Nampaknya egonya sudah jatuh. Tiba-tiba aku rasa diri ini hebat pula kerana berjaya menundukkan ego seorang lelaki.
Baik Ariesa, inilah masanya untuk kau tuntut penjelasan daripadanya. Tanganku cekap mencapai beg galasku, lantas mengeluarkan sehelai kertas kajang.
“Boleh jelaskan ini?” Aku mengunjukkan suratnya petang tadi. Riak wajah Lokman terus berubah tatkala dia melihat surat itu. Pipinya mula berubah menjadi sedikit merah. Wait, that boy is blushing? Unbelievable.
“Apa yang kau nak aku terangkan lagi? I think, everything is clear in that letter right?” Wah, mahu speaking lagi. Aku balas nanti, jangan ternganga.
“Almost everything. Please explain me the last paragraph, the second last sentence. Please!” tegasku sambil menyerahkan surat tersebut kepada Lokman. Dahi lelaki itu berkerut-kerut saat membaca bahagian yang disebut itu. Pipinya mula memerah sekali lagi.
“Err, sebenarnya, memang aku yang… eh tak! Aku tengah serabut tadi so, so err… aku tertulis tadi. Yalah, err takkanlah aku nak cekik… err leher aku sendiri pula kan?” Tergagap-gagap dia merangka ayat, cuba untuk menjelaskan situasi sebenar. Ahah, dah malulah tu.
Satu mata untuk Ariesa dan kosong mata untuk Lokman.
Gelagatnya yang gelabah ternyata berjaya menyejukkan hatiku. Comel juga si Lokman ini bila dia kalut. Aku cuba untuk menahan tawa namun akhirnya terletus ledakan tawaku. Lokman memandangku pelik.
Setelah tawaku reda, aku menyambung kata. “Rileks lah bro, jangan gelabah-gelabah. Peminat-peminat kau tengok tu.“ Jariku menunjuk ke arah sekumpulan pelajar puteri yang sedari tadi memerhatikan kami. Tatkala Lokman mula tertoleh ke belakang, gadis-gadis tersebut mengalihkan pandangan. Itulah, usha-usha orang lagi. Kan dah malu.
Tetapi kira beruntunglah, Lokman pandang mereka. Bukan senang budak hot macam dia nak pandang perempuan. Aku patut terima sijil penghargaan daripada mereka.
“Dahlah, jomlah sambung. Tiba-tiba rasa bersemangat pula nak belajar Matematik.” Aku membunyi-bunyikan jari-jemariku lantas mencapai pensel tekan kesayangan. Terus aku membuat latihan pengukuhan di dalam buku teks.
Setelah lama berdiam diri, suara garaunya kedengaran perlahan. “I’m sorry.”
Pantas aku mengangkat wajah tatkala mendengar kata maafnya. Tangan yang ligat menulis nombor terhenti sebentar. Bibirku pantas mengukir senyuman. “Never mind. Aku pun nak minta maaf sebab buat pasal tadi.”
Lokman mengangguk kecil. Matanya tertancap kembali ke buku latihan fizik miliknya. Mungkin dia masih keliru dengan aku yang tiba-tiba berubah mood.
Ketahuilah Lokman Hariss, tujuh tahun usia perkenalan kita pun kau tak mampu untuk mengenali aku, apatah lagi aku untuk menjadi yang penting dalam diri kau.
LIMA bulan kemudian,
Aku berlari-lari anak terus ke deretan kad buatan tangan yang ditampal di dinding. Mataku ligat mencari ruang-ruang kosong bagi menampal kad di tangan.
Terlihat sahaja ruang kosong, tanganku terus gatal mahu menampal kad keras itu di dinding. Sebaik sahaja kad itu melekat, terus aku bercekak pinggang tanda berpuas hati dengan hasil karya sendiri. Bukan senang tahu untuk Ariesa Adryana untuk membuat kad secantik itu.
Sebenarnya, kad itu merupakan last minute artwork. Petang tadi baru aku ingat bahawa pelajar sekolah kami akan mereka kad-kad ‘Semoga Berjaya’ untuk pelajar-pelajar tingkatan lima sebaik sahaja minggu peperiksaan SPM tiba. Aku juga baru ingat bahawa mentor ‘kesayanganku’ itu merupakan calon SPM, maka terus aku mereka kad sebesar komik untuknya.
Puas juga aku memikirkan ayat untuk ditulis di atas kad berwarna turquoise itu. Akhirnya setelah puas menelaah kad-kad tahun sebelum ini, aku menulis ayat yang ringkas tetapi penuh maksud tersirat. Maksud tersirat yang hanya aku dan dia yang faham.
Dear mentor,
thanks a lot for your help. Thanks you for wasting 8 months for a dumb and stupid mentee like me. Jangan risau, aku dah restu kau. Mesti kau boleh score straight A+ punyalah! Good Luck for SPM!
p/s: AddMaths dan Matematik teras kau mesti A+ tau! Kalau tak aku cari kau sampai dapat.
Lama aku berdiri di situ, merenung segala hasil karya pelajar di sekolahku. Cantik dan kreatif. Tidak seperti kad aku. Buruk dan terlalu ringkas. Tentu Lokman tidak suka kad ini.
Aku mengeluh kasar. Mungkin aku patut cabut sahaja kad ini. Lagipun, Lokman sudah ada banyak kad cantik-cantik yang ditujukan untuknya. Almaklumlah, jejaka terhangat di pasaran asrama puterilah katakan. Semua secret admire nak bagi sokongan padanya.
“Hmm, what did we got here?” Suara garau itu mematikan lamunanku malah membuatkan aku spontan menoleh ke belakang.
Tubuh tinggi itu sedikit membongkok cuba untuk membaca ucapan di sebuah kad berwarna turquoise. Nanti, aku rasa itu…
Dia baca kad aku?! Tak sempat aku nak cabut.
“A dumb and stupid mentee? I admit it.” Lokman mengerling ke arahku dengan senyuman nakal. Aku mencebik bibir.
“Sorrylah, ini je yang mampu aku buat. Bukannya aku sukarela sangat nak buat. Cuma teringat yang mentor aku ini banyak sangat tolong aku, aku pun buatlah kad ini. Kalau kau tak suka, kau boleh je nak buang dalam tong sampah. Takpun, kau recycle je. Tak adalah pencemaran alam berterusan. Lagipun, kau ada banyak lagi kad yang lagi cun dan lawa daripada kad aku. ” Aku mula merapu tahap gaban. Sebenarnya, ia merupakan salah satu cara untuk menghilangkan debaran halus di dalam dada.
Matanya mula meliar ke arah deretan kad yang bertuliskan namanya. Mungkin mahu membandingkan kecantikan kad-kad lain dengan kad ku. Jadi, sebelum hati aku sakit bernanah, lebih baik mengundur diri. Perlahan-lahan aku menapak ke belakang beberapa langkah, cuba untuk tidak membuat apa-apa bunyi.
“Tak cantik pun!” Lokman selamba mengutuk deretan kad yang ditujukan kepadanya. Langkahku jadi terhenti mendengar kutukannya. Terus aku berjalan kembali ke arahnya lantas memukul perlahan lengannya. “Ouch! It’s hurt!” ujarnya, sedikit mengada. Mana mungkin pukulan seperlahan itu mampu menyakitkan lengan sasanya.
“You know what? Among the cards, I love this one most.” Tangannya bergerak memegang sebuah kad lantas ditanggalkan daripada dinding. Terkedu aku melihat perbuatannya.
“Aku nak simpan kad ni untuk aku seorang je.” Lokman menayangkan kad aku kepadaku lantas memasukkannya ke dalam beg sandangnya. Langkahnya terus diatur ke kelas, untuk menghadiri kelas tambahan Biology.
“By the way, thanks for this beautiful card, dumb and stupid mentee.” Dia menjerit kuat tanpa menoleh ke arahku. Terkaku aku di situ, cuba menerima realiti yang sedang terjadi.
“IBU, kenapa rumah sebelah macam kosong je? Mana pergi Uncle Latiff?” Persoalan itu akhirnya aku ungkapkan setelah hampir dua minggu aku bertapa di rumah sempena cuti sekolah akhir tahun. Sebenarnya, aku sedang menunggu Lokman pulang. Iyalah, SPM baru sahaja berakhir semalam. Takkan dia tidak balik rumah lagi?
Ibu yang sedang sibuk menyelak majalah memandang dengan wajah hairan. “Riesa tak tahu ke?” tanya ibu kembali. Majalah Wanita yang dibeleknya ditutup kembali.
Berkerut dahi aku mahu memahami kata-kata ibu. “Tahu apa?”
“Uncle Latiff sekeluarga dah pindah dua minggu lepas. Pindah mana pun ibu tak tahu.” Kata-kata ibu membuatkan rahangku jatuh. Pindah? Tubuhku tiba-tiba menjadi lemah longlai.
“Tapi, kenapa Lokman tak beritahu Riesa apa-apa?” ujarku cuba menahan rasa hati yang dipagut sayu. Ibu hanya menggeleng, tanda kesal.
“Lokman tak beritahu kamu apa-apa? Ya Allah, ibu ingatkan Lokman dah beritahu kamu.” Bertambah luluh hati aku, membuatkan aku spontan bangkit berlari menuju ke bilik.
Masuk sahaja ke dalam bilik, aku terus mengunci pintu. Tubuhku dihempaskan di atas katil bersaiz Queen itu. Mencapai bantal merah kesayangan, terus aku menekup muka, cuba menahan mutiara berharga daripada mengalir. Tanganku menumbuk-numbuk tilam empuk tersebut, namun tentunya tumbukan paduku tenggelam dalan ketebalan tilam tersebut.
Telefon pintar di atas meja pantas dicapai. Jemariku laju menari di atas papan kekunci telefon. Mendail nombor si dia yang aku hafal di luar kepala. Beberapa saat kemudian, aku mulai mencampak telefon ke atas katil. Geram juga mendengar suara operator yang menjawab panggilanku ‘mesra’.
Sedaya upaya aku cuba untuk menahan tangis, tetapi bagai ada sesuatu yang memaksa aku supaya bersedih dan menangisi insiden ini. Setitis manik berharga mulai jatuh membasahi bantal di dalam dakapan.
Puas aku menangis di dalam bilik sendiri. Rasa kesal, sedih dan kecewa berterabur di dalam hati. Bagaimana agaknya aku mahu membuang rasa sayang yang bertapak di hati?
Hampir setahun dia menjadi mentor aku, membuahkan rasa yang tidak pernah aku kira bahawa ia akan muncul. Mungkinkah rasa ini yang membuatkan aku menangisi khabar ini?
Peristiwa tiga minggu yang lalu terus menerus melayang di minda. Tak aku sangka, itu adalah kenangan terakhir aku dengan dia kerana selepas peristiwa itu, dia sibuk dengan peperiksaan SPM.
Aku kira, aku lebih rela hidup dalam dunia mimpi yang indah daripada menghadapi dunia realiti yang kejam ini.
FAIL-FAIL dan dokumen-dokumen sudah berselerak di seluruh ruangan pejabat. Tangan aku pantas membelek satu-persatu mencari satu dokumen penting. Bibirku tidak henti-henti merungut dan membebel. Sekali pandang, seperti makcik yang jual nasi lemak di tepi jalan pula. Aduh, bahaya ini. Sudahlah pukul dua ini aku perlu berjumpa dengan klien penting. Mataku sempat melirik ke jarum jam dan jarum pendek tersebut menunjukkan ke arah angka 12.
Dua jam untuk mencari dokumen itu. Ya, daripada aku membebel macam makcik dan disalah anggap sudah berlaki anak lima, lebih baik aku tarik nafas dan tenangkan diri. Jangan panik, Ariesa. Jangan panik.
Okay, aku tak boleh. Mana perginya dokumen itu?!
Laju tanganku menarik laci meja yang sarat dengan pelbagai ‘harta karun’. Mata melilau mencari-cari kertas bersaiz A4 bertaip tersebut.
“Cik Ariesa? Kenapa bersepah ni?” Satu suara menegur aku dengan nada terkejut. Pantas aku mengangkat muka, melihat tuan punya suara. Lega hatiku melihat pembantuku, Kak Ayuni melangkah masuk ke dalam bilik. Aku pantas bangun dari tempat duduk, membetulkan sedikit lilitan selendang yang sudah senget.
“Kak Ayuni ada nampak tak dokumen Encik Khalil? Saya ada temujanji dengan dia pukul dua ni.” Lembut aku menuturkan suara tanda menghormati Kak Ayuni yang tua beberapa tahun daripadaku. Walaupun aku adalah orang atasannya, aku tidak pernah lupa untuk menghormati orang yang lebih tua daripadaku tanpa mengambil kira pangkat. Mungkin itu adalah salah satu pengaruh sewaktu bersekolah asrama dahulu.
“Ya Allah, dokumen itukan saya letak di dalam fail peribadi Cik Ariesa. Saya dah beritahu cik pagi tadi,” ujarnya sedikit menggeleng. Aku menggaru kepala yang tidak gatal itu. Tanganku beralih mencapai fail peribadiku di atas meja. Setelah menyelak beberapa kali, bibirku mula menyimpulkan sengihan. Pandanganku dihalakan ke arah Kak Ayuni sambil tersengih seperti kanak-kanak ribena.
“Hehe, adalah pulak akak. Terima kasih.” Aku mengucapkan kata-kata tersebut sambil melangkah perlahan fail-fail di lantai. Kak Ayuni hanya mampu tersenyum lantas berkata, “Baik Cik Ariesa bertolak sekarang. Nanti jalan jammed kan susah. Tak pasal saja cik lambat nanti. Pasal bilik ini, biar saya yang kemas.”
Terlopong aku mendengar tawaran itu. Terus aku mengangguk laju lantas mencapai tas tangan di kerusi. Tidak dilupakan, fail peribadi berwarna hitam itu dibimbit kemas. “Terima kasih akak! Ni saya makin sayang kat akak ni,” ujarku lantas mengatur langkah ke pintu. Kak Ayuni hanya mampu menggeleng kepala lantas mula mencapai segala fail-fail dan dokumen yang berselerak di atas lantai.
Sebaik sahaja terlihat kereta Myvi berwarna kuning itu, terus aku menekan punat khas di atas kunci kereta. Terus aku menerobos masuk ke dalam dan menghidupkan enjin. Moga-moga sempatlah aku sampai sebelum pukul dua petang.
“AKU rasa kau patut berhenti termenung, Ariesa.” Suara garaunya membuatkan aku mengangkat wajah. Senyuman yang terukir menjadi lebih lebar daripada sebelumnya.
“Macam tak percaya.” Sebaris ayat itu membuatkan dia mengeluh kasar. Kertas putih di tanganku dirampas kasar.
“Hei!” ujarku spontan. Mungkin kerana terkejut dengan perlakuannya. Tanganku pantas mencubit lengan sasanya. Berkerut dahinya menahan pedih.
“Woi! Mentang-mentanglah dah dapat ‘A’, nak cubit-cubit mentor pulak. Derhaka tahu,” ujar Lokman sambil menggosok lengannya. Aku hanya tersengih gembira. Mataku ralit merenung markah ujian Matematik yang terbaru. Keputusan yang cukup membanggakan aku dan dia.
Aku tidak henti-henti tersenyum, mengenangkan pujian guru Matematiknya di kelas sebentar tadi.
“Ariesa, tahniah! Markah awak adalah antara yang tertinggi di dalam kelas. Teruskan usaha,” kata Puan Waheeda tatkala aku bangkit mahu mengambil kertas ujian. Sekelip mata kelas tersebut sudah kecoh dengan pelbagai bisikan.
Aku berjalan ke kelas dengan penuh bangga. Senyuman lebar tidak lekang di bibir. Mengerling ke arah Ami, Ami menunjukkan isyarat ‘one thumbs up’ kepada aku. Aku mencapai kertas yang diserahkan dengan penuh kegembiraan.
Habis kelas, aku terus berlari mencari Lokman. Aku terus ke belakang blok akademik yang jarang sekali dia pergi. Entah mengapa, firasat aku mengatakan bahawa dia ada di situ. Dan tepat sekali, Lokman ada di atas rumput, sedang termenung melihat pohon besar di situ.
Ternyata dia juga gembira mendengar khabar tersebut. Daripada keadaanya yang sedang melayan perasaan berbaring di atas rumput hijau, boleh membuatkan dia bersila melihat kertas itu.
“Lokman, terima kasih ya? Kalau bukan sebab kau, aku mesti tak dapat markah seperti ini.” Aku berkata setelah lama berdiam diri. Lokman yang sedang bermain dengan seekor kucing putih yang tiba-tiba muncul itu sedikit tersentak.
“My pleasure, dear,” ujarnya pendek namun matanya tepat merenung wajahku. Ya Allah, sudahlah ketika itu pipi aku sudah mula memerah. Bunga-bunga cinta mulai terbit dalam jiwa, mengharap saat ini tidak akan berlalu.
Detik-detik yang paling berharga adalah detik bila aku bersama dia, yang telah menyimpan kemas hatiku di dalam hatinya.
“CIK Ariesa, boleh masuk ke dalam sekarang.” Kata-kata kerani itu melenyapkan lamunanku, membuatkan aku spontan berdiri. Malu juga apabila melihat kerani tersebut melihat aku mengelamun. Haish, Ariesa. Jangan libatkan dia semasa bekerja. Lagipun, bukankah dia telah meremukkan hati kau. Buat apa fikir pasal dia lagi?
“Terima kasih.” Aku membalas kata-kata kerani tersebut sambil tersenyum manis.
Hakikatnya, itu hanyalah senyuman yang penuh dengan ‘ketidakikhlasan’. Aku sudah hilang tenaga mahu melakukan apa-apa. Peristiwa tengah hari tadi asyik bermain di minda. Tidak sangka peristiwa itu mampu mencuri sedikit sebanyak tenaga aku. Sedaya upaya aku mengumpul semangat dan kekuatan agar aku tidak moody semasa bertemu dengan klien itu.
Dengan beberapa buah fail di tangan, aku melangkah masuk ke dalam ruang pejabat itu dengan debaran menggila. Kenapa aku rasa berdebar ini? Sudah berjuta kali aku bertemu dengan klien, tak ada pula menggeletar seperti ini.
“Assalamualaikum.” Aku memberi salam sebaik sahaja aku melihat kelibat seorang lelaki di atas kerusi. Lelaki korporat itu terus mengangkat muka dengan senyuman manis terukir di bibir.
Fail-fail di tangan terjatuh serta merta. Habis berterabur di atas lantai. Namun, aku seperti terkaku. Terpaku melihat seraut wajah di hadapanku. Kenapa… kenapa kau baru muncul sekarang?
“Cik Ariesa Adryana, please have a seat.” Suara itu menegurku. Ya Allah, itu memang dia…
Lama juga aku berdiri di hadapan meja itu. Cuba untuk menerima hakikat yang sedang berlaku. Mengingatkan apa yang dia lakukan 11 tahun lampau, egoku mula naik menggunung. Lelaki penipu sepertinya harus aku beri sedikit pengajaran. “Saya rasa saya buat appointment dengan Encik Khalil, bukan dengan Encik Lokman Hariss. Maafkan saya, saya minta diri dulu.”
Aku mula mengutip fail-fail di lantai namun helaian kertas yang berterabur membuatkan proses mengutip menjadi panjang. Sedang aku sibuk mengutip segala dokumen-dokumen itu kembali, sebuah tangan menghulurkan sehelai kertas yang dikutipnya. Aku merampasnya kasar, lantas bangkit menuju ke pintu.
Belum sempat aku memulas tombol pintu, pergelangan bajuku terasa seperti ditarik lembut. Terhenti segala pergerakanku apabila mendapati tangannya menarik lembut pergelangan tanganku.
“Ariesa Adryana.” Lirih suaranya menyebut namaku. Terus hilang segala kemarahanku, digantikan dengan rasa indah yang sukar untuk diungkapkan. Namun, otak cepat-cepat mengingatkan tindakannya dahulu menyebabkan aku terseksa dengan pemergiannya.
Tolong jangan sekali-kali kalah dengan ayat-ayat manis seorang lelaki, Ariesa.
“Encik Lokman, tolong jangan pegang tangan saya,” tegasku. Kata-kataku nyata tidak memberi kesan kepadanya. Dia terus memegang pergelangan bajuku erat sambil matanya merenungku.
“Kita baru sahaja jumpa dan awak nak pergi macam tu saja?” Lokman memandangku, meminta jawapan. Aku cuba untuk tidak bertentang mata dengannya. Sakit hatiku mendengar kata-katanya.
“Ya, dan saya akan pergi sama macam awak pergi tinggalkan saya macam tu saja dulu,” ujarku lantas merentap tanganku kasar. Langkahku diatur keluar dari pintu dengan 1001 satu perasaan yang bercelaru.
“Ariesa!” jeritnya sehinggakan kerani yang berada di luar pintu itu memandang pelik ke arah kami.
Lari daripada klien sendiri adalah perkara paling gila pernah aku lakukan sepanjang bekerja. Namun, aku rasa aku bukan lari daripada klien. Aku melarikan diri daripada seorang lelaki yang meninggalkan aku saat rasa hati mula berputik.
Aku pantas menerobos masuk ke dalam kereta. Air mataku deras mengalir ke pipi. Tanganku memukul-mukul stering kereta. Lokman Hariss muncul semula. Muncul sebagai seorang lelaki dewasa yang jauh lebih matang berbanding dahulu.
Aku memang mengharapkan kepulangannya, tetapi entahlah. Aku merasakan lelaki itu juga perlu memahami ertinya sakit hati.
Satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa sakit hati adalah menangis. Tetapi, aku tidak mampu. Aku sudah penat menangis berguling-guling di atas katil selama 11 tahun.
Air mineral di dalam beg tangan dicapai. Perlahan-lahan, aku meneguk air tersebut. Terasa lega sedikit apabila air mengalir perlahan di tekak. Sudah menjadi kebiasaan aku apabila perasaan terasa bercelaru, aku mencapai air mineral untuk menenangkan diri.
Aku cuba menghidupkan enjin kereta lantas terus memandu kereta Myvi kuning itu pulang ke rumah yang aku sewa bersama Nurul, rakan baik semasa di universiti. Lebih baik aku pulang ke rumah tenangkan diri daripada aku mengamuk tidak tentu fasal di pejabat.
“WOI, awal kau balik?” ujar Nurul tatkala aku menutup pintu rumah perlahan. Mulutnya tidak henti-henti mengunyah bertih jagung yang entah dari mana dia dapat. Matanya tertancap ke arah televisyen yang sentiasa bercahaya.
“Awal ke?” soalku sambil mengerling jam tangan hitam di pergelangan tangan. Wah, rekod baru. Pertama kali aku sampai rumah pukul 6 petang. Kebiasaannya, aku tiba di rumah pada jam 9 malam. Nurul hanya mengangguk kecil lantas matanya difokuskan kembali ke televisyen.
“Tak nak join ke?” Nurul menyoal aku perlahan, merujuk kepada filem yang ditayangkan di televisyen itu. Aku mengerling ke arah televisyen nipis tersebut, lantas menggeleng perlahan. “Sorry sis, aku letihlah. Naik bilik dulu.”
Nurul hanya mengangguk perlahan. Gadis tersebut bekerja sebagai seorang guru sekolah menengah. Sesi pengajarannya pula hanyalah pada waktu pagi sehinggalah tengah hari. Jadi, pada waktu petang sehingga malam, dia bolehlah bermalas-malasan di rumah. Kadang kala, dia keluar berdating dengan tunang kesayangan, menguruskan hal perkahwinan mereka yang akan berlangsung dua bulan lagi. Bahagia betul hidupnya. Kalaulah hidup aku sepertinya…
Aku pantas memanjat anak tangga. Satu persatu. Langkahku diatur menuju ke bilik rona ungu dan putih. Sememangnya, warna tersebut menjadi kegemaranku semenjak di bangku sekolah lagi.
Aku pantas mencapai laptop di atas meja belajarku yang sudah lama tidak berpenghuni. Almaklumlah, tuan punya meja sudah bekerja. Mana sempat nak menelaah apa-apa buku seperti sewaktu di universiti dahulu. Nasib kau lah meja, kenalah tunggu tuannya ambil Master, baru nasib kau terbela sedikit.
Sekian lama menerokai dunia maya, aku mulai membaringkan badan di atas katil. Laptop di hujung kaki aku biarkan terbuka. Wajah dia terpampang di minda. Mengingatkan apa yang dia katakan sebentar tadi, membuat aku luluh dan hampir memeluknya. Rindunya aku kepada dia tidak mampu diungkap dengan kata-kata.
Lagu ‘Setengah Mati Merindu’ yang terbit dari telefon pintarku mematikan lamunanku. Ah, bagus. Kenapalah aku set lagu ini jadi nada dering? Rasa macam kena perlilah pulak. Perlahan-lahan aku mencapai telefonku, menekan butang hijau di skrin.
“Helo, siapa ni?”
“Helo. Umm, boleh cakap dengan cik Ariesa?” Suara perempuan ni macam pernah dengar lah…
“Saya bercakap. Ini siapa?”
“Ariesa! Ini akulah, Ami Farihah. Ingat tak?” Bulat terus mata aku mendengar kata-kata gadis itu.
“Ami?! Ya Allah, lama lost contact. Kau kat mana sekarang?”
Kedengaran gelak kecil dari hujung talian. “Ceh, soalan klise. Tanyalah aku single ke, dah tunang ke, dah ada suami kaya ke. Ni tak, tanya aku kat mana. Boring.”
Aku tergelak besar. Ya Allah, rindunya aku pada dia ni. “Alah, macam tak kenal je aku ni. Seriuslah, nanti boleh jumpa-jumpa.”
“Heh, aku kat KL je. I’m working as an accountant. You?”
“Aku? Aku kerja kat syarikat ayah aku. Well, you know, when we had a father who has his own company and the father want us to work at his company. Pewaris syarikatlah konon.” Kata-kataku mengundang tawa dari bibirnya.
“Eleh, untunglah tu. Bila kau dah jadi big boss nanti, jangan lupa tawarkan kerja kat aku. Haha, just kidding girl,” guraunya, sengaja mahu menceriakan suasana.
“Kalau betul pun apa salahnya. Boleh kerja sebumbung,” ujarku penuh kegembiraan. Seronok juga kalau ada kawan kerja sekali dengan kita.
“Okay. Make sure you do it. Oh yes! Lupa nak tanya. How‘s your Lokman? Mesti makin gemukkan pakcik tu?”
Gelak tawaku terhenti tatkala dia menyebut nama lelaki itu. Aku menelan air liur. Patutkah aku cerita?
Sepanjang baki tiga tahun di sekolah menengah setelah Lokman keluar dari sekolah, aku langsung tidak bercerita kepada Ami tentang Lokman. Setiap kali Ami bertanya perihal dia, aku cuba mengalih topik. Apabila dia mula mendesak, aku memberitahu yang kononnya Lokman sibuk dengan urusan belajarnya jadi dia tiada masa untuk meluangkan masa denganku.
“Err, oh yes. Kau dah ada boyfriend ke?” Kalut aku mengajukan soalan kepadanya. Sedaya upaya aku cuba untuk mengalih topik. Di hujung talian, tawa bergema di segenap ruang.
“Hey, hey. Cuba tukar topik ya. Aku? Dah bertunang pun. Nanti aku kenalkan tunang aku kat kau. Kau tu, bila si Lokman nak masuk meminang?” ujarnya sedikit teruja. Aku menelan air liur. Aduh, nak jawab ke tak?
“Wah, dah bertunang dah kawan aku ni. Tahniahlah. Bila majlisnya? Jangan lupa jemput, aku kempunan nak makan nasi minyak ni.” Aku pura-pura riang. Beberapa ketika, Ami terdiam membisu.
Akhirnya, Ami bersuara menyebabkan aku hampir menitiskan air mata. “Ariesa, aku tahu kau ada masalah dengan dia. Sejak dari dia keluar dari sekolah lagi kan? Ceritalah. Kau akan sengsara pendam cerita tu seorang diri.”
Satu perkara yang membuatkan aku terharu, Ami Farihah mempunyai naluri seorang kawan yang amat kuat. Selama lima tahun satu sekolah dengannya, dia sentiasa dapat kesan masalah yang aku pendam sendiri. Entah detektif profesional mana entah dia upah, sehingga dia jadi begitu.
“Sebenarnya Ami…” Aku terus bercerita panjang dari awal sehingga akhir. Tersentak Ami mendengar ceritaku.
“Tadi, aku pergi jumpa klien, dan aku tak sangka yang klien tu adalah…” Aku tidak jadi menyambung kata. Tentulah Ami sudah dapat meneka siapa gerangan orang itu.
“Adalah Lokman kan?” teka Ami. Aku terdiam. Keluhan terbit dari bibir Ami.
“Ariesa, kadang-kadang kita perlu melupakan kepahitan yang lalu, untuk memperoleh kemanisannya sekarang.” Kata-kata Ami membuatkan aku tersentak, memikirkan kewajaran tindakan aku tadi.
Keliru. Ini salah aku yang tidak mahu memaafkan atau salah Lokman yang telah melukakan?
SEBULAN berlalu selepas pertemuan semula aku dan Lokman. Hidup aku juga aman setelah abah mengarahkan pekerja lain menguruskan projek dengan syarikat Encik Khalil. Bukan aku tidak mahu handle projek itu, tetapi aku takut untuk bertemu dengan dia, yang berkemungkinan besar bekerja di syarikat itu.
Misi bulan ini adalah melupakan Lokman Hariss Abdul Latiff.
Hujung minggu itu, aku mengambil keputusan untuk pulang ke rumah ibu dan abah. Sudah lama juga aku tidak bertemu dengan mereka. Perlahan-lahan aku memandu kereta Myvi kuning menuju ke rumah tempat aku membesar.
“Assalamualaikum ibu.” Aku memberi salam tatkala melihat kelibat ibu sedang menyiram pokok bunga di laman. Ibu menoleh sejenak, lantas bergerak mendekati aku.
“Waalaikumussalam. Ha, balik pun anak ibu seorang ini. Ibu ada hal nak cakap dengan kamu sekejap lagi,” ujar ibu setelah aku mencium tangan tua itu.
Kata-kata ibu menyebabkan tindakan aku terhenti. Aku memandang ibu pelik. “Ada apa ibu?” Ibu membalas pertanyaanku dengan senyuman manis.
“Masuk dulu, nanti kita bincang. Abang! Anak kita dah balik!” Ibu mencapai beg pakaianku lantas bergerak memasuki rumah. Langkahku diatur ke ruang tamu di mana abah sedang membaca surat khabar. Pantas aku menyalami abah.
“Abah sihat?” Aku sekadar berbasa-basi. Abah mengangguk kecil lalu menyambung pembacaannya.
Tatkala aku mahu bangkit bergerak ke bilik, abah bersuara. “Duduk sini. Ada benda yang abah dan ibu nak bincangkan.” Terus aku duduk di sofa, berhadapan dengan abah. Ibu datang membawa dulang air dan sedikit kudapan.
Pandangan ibu dan abah yang dihalakan serentak membuatkan aku resah. Perlahan-lahan aku menyisip sedikit air milo yang disediakan bagi menghilangkan gementar.
“Sebenarnya, ada apa ibu, abah?” Aku mulai mengajukan soalan. Tidak tahan aku duduk diam ditemani jelingan daripada mereka.
Tawa abah meletus kuat. Terkejut aku melihat abah tiba-tiba sahaja ketawa. Terkena angin apa pula orang tua ini?
“Sorry. Tergelak pulak abah, tengok muka kamu dah cuak. Abah nak cakap, ada rombongan datang merisik kamu semalam. Abah dan ibu dah terima dah.”
“Apa?! Kenapa tak tanya Riesa dulu?”
“Perlukah?” ujar ibu sedikit sinis. Menyirap darahku ketika itu, namun memikirkan mereka adalah ibubapaku, aku cuba bertahan.
“Ibu, ini masa depan Riesa. Kalau Riesa tak bahagia dengan dia macam mana?” ujarku lembut. Ibu menggeleng lembut, menafikan apa yang aku katakan.
“InsyaAllah, kamu akan bahagia. Ibu dan abah kenal rapat dengan tunang kamu tu.” Tunang? Maknanya aku dah bertunang?
Ibu bangkit menyerahkan sebuah kotak baldu kecil kepadaku. Sebaik sahaja kotak itu dibuka, sebentuk cincin belah rotan yang begitu indah dan cantik disarungkan ke jari manisku. “Ibu yakin kamu akan bahagia,” bisik ibu perlahan ke telingaku.
Aku mengangguk kecil, redha dengan apa yang terjadi. Mungkin inilah salah satu cara untuk aku melupakan Lokman, iaitu dengan bertunang dengan entah lelaki mana yang aku tidak kenali.
GEMBIRA sungguh wajah Nurul saat dia telah sah diijabkabulkan dengan lelaki pilihannya. Gadis berkaca mata itu tidak lekang daripada senyuman saat bersalaman dengan semua jemputan yang hadir.
Saat dia bersalaman denganku, aku bertindak untuk memeluknya erat. “Tahniah, semoga kekal ke anak cucu. Tinggallah aku seorang kat rumah tu.”
Nurul ketawa mendengar pernyataanku. “Kalau tak nak tinggal seorang, cepat-cepatlah kahwin!” Dia menepuk-nepuk bahuku. Aku hanya mampu mengukir senyum.
Sebulan lagi, aku bakal melangsungkan perkahwinan dengan lelaki pilihan ibu. Sebulan aku bertunang, aku masih belum mengenali tunangku. Malah, wajah dan namanya juga aku belum tahu. Ibu kata, nanti bila tiba masanya aku akan bertemu dengan dia juga.
Hal-hal perkahwinan juga diuruskan oleh tunangku sendiri. Aku hanya diminta pergi ke sebuah butik pengantin di KL bersama ibu dan mencuba beberapa helai pakaian pengantin yang telah tunangku pilih. Mudah betul hidup aku.
Pulang dari majlis akad nikah Nurul, telefon pintarku berdering. Terus aku menekan butang hijau apabila melihat nama dan gambar ibu terpampang di skrin.
“Ariesa, balik sekarang. Malam nanti, tunang kamu nak datang,” ujar ibu teruja, menyebabkan aku menggeletar hebat. Setelah memberi persetujuan, aku terus bergerak ke bilik, memilih beberapa helai baju untuk dibawa bersama. Setelah itu, barulah aku mencapai kunci kereta dan bertolak ke rumah ibu.
RIUH rendah kedengaran daripada ruang tamu di tingkat bawah. Rancak benar ibu berbual-bual dengan bakal besannya. Aku hanya mampu berteka-teki dari tingkat atas. Masih terngiang-ngiang kata-kata ibu sebentar tadi.
“Kamu jangan turun ya. Nanti bila ibu datang panggil, baru turun.”
Aku mengeluh lemah. Bilalah ibu nak jemput aku ni? Aku pun nak tengok siapa lelaki yang ibu bangga-banggakan sebelum ini. Perlahan-lahan aku bangkit dari katil, merapikan tudung bawal yang terletak elok di kepala.
Ketukan di pintu membuatkan aku spontan menoleh ke arah pintu. Wajah ibu terpacul dari muka pintu. “Jom turun.”
Aku mengangguk kecil sebelum melihat refleks diri yang berbaju kurung pahang di cermin. Perlahan aku mengekori ibu, sedaya upaya cuba untuk menonjolkan kesopanan tahap gadis melayu terakhir. Tatkala menuruni tangga, aku melihat sepasang suami isteri yang amat aku kenali.
“Auntie Jun?” ujarku lantas bergerak menyalaminya. Auntie Jun tersenyum manis. Auntie Jun ini adalah ibu kepada Lokman. Nanti dulu, kalau bakal ibu mertuaku adalah Auntie Jun, jadi…
Aku menoleh ke sebelah Auntie Jun bagi melihat wajah tunanganku sendiri. Terkedu aku melihat senyuman di wajah tampan itu. “Lokman?!”
Spontan aku menuturkan nama itu. Tatkala itu, abah sudah tergelak besar, seperti bersepakat dengan Uncle Latiff. Ibu dan Auntie Jun juga sudah tersengih-sengih, cuba untuk tidak ketawa. Lokman sendiri sudah tersenyum meleret, kegembiraan terpancar di wajahnya.
“Ibu, abah apa semua ni? Uncle, Auntie?” Aku bertindak untuk mengajukan persoalan secara umum. Sesiapa, tolonglah terangkan apa yang berlaku sekarang.
“Nak terangkan apa lagi? Kan dah terpampang semuanya,” ujar abah, masih dalam mood mengusik. Aku sedikit mencebik, geram dengan abah yang tidak serius itu. “Abah…” rengekku sedikit manja.
“Patutlah Lokman suka, manja betul si Ariesa ni.” Kata-kata Uncle Latiff menghentikan segala pergerakanku, menyebabkan pipi ini menjadi merah. Lokman yang sedari tadi merenungku, tergelak besar mendengar kata-kata ayahnya.
Sepanjang pertemuan itu, aku langsung tidak bersuara. Cuma apabila ditanya, aku hanya menjawab sekadar menjaga hati mereka. Lokman sendiri diam membisu. Baguslah tu, tak adalah aku merana perlu berbual dengannya.
Jarum jam menunjukkan angka 10 malam. Menyedari hal itu, Auntie Jun dan Uncle Latiff mengambil keputusan untuk meminta diri. Lokman juga sudah bangkit memegang kunci kereta.
Saat itu, aku sudah menarik nafas lega. Berakhirlah kesesakan jiwa aku sebentar lagi. Baru sahaja ingin meminta diri mengangkat cawan-cawan ke dapur, ibu sudah menahan. “Tak payah angkat. Itu, Lokman mahu bercakap dengan kamu.”
Tanpa aku sedar, aku sudah menepuk dahi. Reaksi luar sedar aku itu membuatkan ibu tergeleng-geleng lantas bangkit membawa cawan-cawan ke dapur. Perlahan-lahan aku menapak ke laman rumah yang diterangi dengan lampu laman yang berbentuk bulat.
“Ada apa?” ujarku tanpa memandang wajahnya. Dari tempat aku berdiri, aku melihat ibu dan abah mengintip dari dalam rumah. Alahai, ada sajalah ibu abah ini.
“Pandanglah muka abang dulu…” Lembut Lokman bersuara. Abang? Kena panggil dia abang ke? Sebelum ini, aku hanya pernah guna ‘aku kau’ dan ‘saya awak’ dengannya. Tiba-tiba kena guna abang ni, apa kes pula?
Aku cuba untuk memaksa diri cuba untuk bertentang mata dengannya. Aduh, melihat senyumannya sahaja sudah buat aku cair, apatah lagi kalau aku bertentang mata dengannya. Boleh lebur agaknya!
“Tak nak peluk abang ke? Dengar cerita, ada orang tu meroyan rindu sebab abang tinggalkan dia.” Usikan Lokman menyebabkan aku menghadiahkan jelingan ‘manja’ kepadanya.
“Tunggulah kahwin nanti!” balasku sedikit tegas. Hakikatnya aku sudah mahu tergelak mendengar usikannya. Dasar miang!
“Riesa ikhlas tak nak kahwin dengan abang?” Sengaja dia mendugaku. Aku menjelingnya sekilas.
“Kalau saya tak ikhlas pun, awak tetap akan kahwin dengan saya kan?” Aku membalas pertanyaannya dengan soalan. Mana taknya, persediaan perkahwinan semua sudah diatur. Takkan nak batal. Mahu rugi beribu-ribu ringgit!
Dahinya berkerut seribu, sebelum gelak tawanya meletus kuat. “Memanglah, tapi abang cuma nak sebuah jawapan.”
“Jawapan yang menyakitkan hati, atau jawapan yang sedap didengar?” Aku menduganya. Lokman tersengih. “Mestilah jawapan yang sedap didengar…”
Aku mencebik. “Kalau macam tu, mesti awak dah tahu jawapannya.” Aku berpaling ke belakang, mahu meninggalkannya. Beberapa langkah aku menapak, dia sudah bersuara.
“Yes! Thank you sayang!” jeritnya penuh keterujaan. Kedengaran bunyi tapak kakinya berlari bergerak ke kereta. Tanpa sedar, aku mulai mengukir senyuman.
Benar kata Ami, kadang-kadang kita perlu melupakan kepahitan yang lalu, untuk memperoleh kemanisannya sekarang.
“AKU terima nikahnya Ariesa Adryana binti Hishamudin dengan mas kahwin dua ratus dua puluh ringgit tunai.” Dengan sekali lafaz, termeterailah ijab dan kabul, menandakan aku sah menjadi seorang isteri.
Seperti tidak percaya, gadis tidak matang berusia 25 tahun ini sudah bersuami. Dan suaminya pula adalah lelaki yang pernah mengharu-birukan hidupnya kira-kira 11 tahun lalu.
Majlis tengah hari tadi ternyata telah mengambil hampir separuh tenagaku. Terus aku masuk ke bilik, menyalin pakaian pengantin dengan t-shirt lengan pendek dan seluar track hitam. Sebelum bergerak ke luar bilik, aku mulai ragu-ragu dengan penampilan aku. Tidak mengapa ke aku pakai baju ini saja keluar?
Alah, bukan ada orang lain pun. Yang ada cuma ibu, abah, mama, ayah dan sang suami saja. Adik Lokman, Faiz sudah pulang ke kampusnya. Mahu buat persediaan ujian, katanya. Aku terus bergerak memulas tombol pintu.
Tiba-tiba bahuku terasa sakit apabila aku terasa seperti terlanggar orang. Terus aku mendongak bagi melihat tubuh tinggi itu. Siapa lagi yang tinggi seperti itu kalau bukan Lokman?
“Nak pergi mana sayang?” Dia mengelus rambutku lembut. Aku menelan air liur. Aduh, dah nak jadi Romeo ke dia ni?
“Err, nak, nak pergi dapur…” ujarku tergagap-gagap. Gementar lah pulak.
Lokman meraih tanganku lembut lantas menarik aku masuk ke bilik. “Tak payah, abang ada something nak cerita kat sayang.” Dahiku mulai berkerut seribu. Apa benda dia nak cerita ni?
“Duduk.” Lokman mengarahku. Terus aku duduk di birai katil. Tanganku masih diusap lembut olehnya. “Ada apa, abang?” Aku sedikit teragak hendak memanggilnya abang.
“Abang minta maaf.” Sebaris kata itu aku kira tulus dari hatinya, sehingga aku mendapat kekuatan untuk bersuara.
“Untuk?” Ceh, kekuatanlah sangat. Sepatah je kau sebut, Ariesa.
“Abang minta maaf, abang tinggalkan sayang dulu. Abang sendiri tak tahu pasal hal tu. Perpindahan tu perpindahan mengejut. Abang balik cuti tu je, tup-tup barang abang dah kemas dan ayah kata kami kena pindah. Tak sempat nak inform kat sayang.”
Kata-kata Lokman membuahkan senyuman di bibir. Sungguh, aku sudah melupakan hal itu. “Riesa maafkan abang. Riesa sendiri rasa Riesa tak matang gila nak marah-marah kat abang. Maafkan Riesa jugak ek?”
Lokman menggeleng-geleng lembut. “Abang tak habis lagi.”
Keningku diangkat sebelah. Mataku menatap wajahnya mahu menuntut penjelasan.
“Sebenarnya, err abang dulu selalu juga contact dengan Ami.” Sebaris kata itu ternyata berjaya membuatkan aku tersentak. “What?!”
Tanganku pantas memegang kedua lengannya lantas menggoncang-goncangkan tubuhnya. “Abang ada contact dengan Ami sepanjang abang pindah tu? Habis tu, kenapa Ami asyik tanya Riesa pasal abang je?”
Mungkin kerana rimas, Lokman mulai mencengkam lenganku lembut. Sepenuh tenaga dia cuba untuk menghentikan pergerakanku. “Sayang, sayang rilekslah! Sakitlah abang.”
Terus aku berhenti menggoncang tubuhnya lantas mempamerkan sengih. Tangan kasarnya yang aku genggam erat membuatkan dia menyimpul senyuman manis.
Dia masih diam seribu dengan senyuman manis. Lama sekali. Aku pula, masih ternanti-nanti tutur kata dari bibirnya. Aku mengetap bibir.
“Abang… cepatlah cerita…” rengekku manja. Lokman tergelak kecil lantas mencuit hidungku.
“Abang just contact dia untuk tahu keadaan sayang. Abang risau jugak, kalau sayang tu buat benda tak patut bila abang pindah…” Lokman mengerlingku nakal di hujung kata.
“Ceh, perasan je.” Aku mencebik. Lokman hanya ketawa.
“Sebenarnya, abang yang suruh dia berlakon tak tahu apa-apa cerita tentang abang depan sayang. Tak naklah kantoi.” Aku mulai mencubit lengannya manja.
“Abang jahat…” rengekku manja sambil memukul-mukul lengannya lembut. Lokman mulai mengukir sengihan nakal.
“Senja-senja macam ni lah sayang nak goda abang.” Sebaris kata itu membuatkan pipi aku memerah malu, pantas bangkit menuju ke ruang tamu yang tiada penghuni. Ah, malunya!
Sedang aku seronok menonton cerita kartun di atas sofa, Lokman pantas mengambil tempat di sebelah lantas meletakkan kepalanya di atas pehaku. Terus aku kaku, keras seperti ais. Apa kena pulak mamat ni?
“Sayang…” ujar Lokman manja sambil mengelus rambut panjangku. Alamak, apa aku nak buat ni?
“Sayang…..” panggilnya lagi, kali ini dalam nada sedikit merayu. Tubuhku terus tegak, bibirku teragak-agak mahu menjawab panggilannya. Lokman mulai tersengih melihat riak wajahku. Terus dia bangkit dari ribaku lantas duduk rapat denganku.
“Alahai, diamnyalah darling abang ni. Ni rasa nak..” Lokman berkata lantas mencium pipiku lembut. Ya Allah! Masa tu, aku sudah tak senang duduk, rasa nak lari pecut laju-laju.
“Baik sayang bersuara, or I’m gonna to lift you to our bed right now.” Lokman mulai mengugut manja. Mendengar ugutannya, membuatkan bulu romaku terus meremang dan suaraku mulai kedengaran.
“Abang nak apa?” Akhirnya! Aku berjaya melantunkan satu pertanyaaan kepada suami tercinta. Tahniah Ariesa Adryana.
Lokman tersengih nakal. Alamak, petanda bahaya ini. “Abang nak… sayang!” Lokman terus mencempung tubuhku lantas dibawa ke kamar pengantin. Jeritanku memenuhi di segenap ruang di ruang tamu.
“Abang!”
Sejujurnya, aku sedang bahagia di dalam dunia romantis ciptaan seorang lelaki bernama Lokman Hariss. Seorang lelaki yang telah banyak mengajar seorang gadis tidak matang mengenai kehidupan.
BANGUNAN sekolah menengahku ditatap penuh rindu. Ami di sebelah sudah mulai menggengam tanganku erat. “Jom, Ariesa.”
“Jom!” ujarku sedikit bersemangat lantas berlari anak ke bilik guru. Meski sudah sudah hampir 10 tahun aku tidak menjejakkan kaki ke sekolah itu, aku sudah masak dengan keadaannya.
“Assalamualaikum cikgu!” Aku memberikan salam kepada guru kesayanganku, Puan Waheeda. Guru berbaju kurung Pahang itu menoleh lantas tersenyum melihat kami berdua.
“Ya Allah, Ariesa dan Farihah. Lama tak jumpa kamu,” tutur Puan Waheeda. Saat itu, tawaku seperti mahu meletus. Mana tidaknya, Puan Waheeda memanggil Ami dengan nama Farihah. Lucu juga mengenangkan guru ini yang merupakan satu-satunya guru yang memanggilnya dengan nama itu.
“Tak sangka juga cikgu masih mengajar di sekolah ini.” ujar Ami sambil mencium tangan guru tua itu. Setelah Ami, aku mengambil giliran untuk bersalaman dengannya.
“Cikgu sayang nak tukar sekolah lain. Lagipun cikgu sekarang Penolong Kanan sekolah.” ujarnya bangga. Aku sendiri sudah teruja mendengar berita itu. “Iya cikgu? Wah, dah naik pangkat lah ni. Kasilah kami duit raya cikgu.” Aku mulai merapu.
Ami memukul lenganku manja. “Woi, tak tahu malulah kau. Maaflah cikgu. Dia ni sejak kahwin memanglah sengal sikit.” Aku tersengih sendiri.
“Cikgu dah tahu dah si Ariesa ni dah kahwin. Ha Ariesa, laki kamu mana? Tak datang sekali ke?” soal Puan Waheeda bertalu-talu. Aku tergelak kecil melihat kesungguhannya.
“Ehem, cikgu lah ni. Nak jumpa cikgu punya pasal, ditinggalnya saya dengan si comel ni.” Sebuah suara menegur kami dari belakang membuatkan kami serentak menoleh.
Lokman yang sedang memimpin putera sulung kami, Aazad Lutfil Hadi pantas mendekatiku. Puan Waheeda sudah terbeliak matanya melihat Lokman yang mulai merangkul erat pinggangku.
“Aazad, salam cikgu abi dan ummi.” Lokman mengarahkan Aazad yang baru berusia 2 tahun itu. Terus anak kecil itu berjalan perlahan ke Puan Waheeda lantas mencapai tangan guru tua itu.
“Lokman ke ni? Hei, dah besar dah budak nakal seorang ni. Tapi kan, comel betul anak kamu berdua.” Puan Waheeda mulai mencubit-cubit pipi tembam Aazad. Aku dan Lokman sudah berpadu tenaga menghamburkan tawa.
“Tengok siapa abi dia, cikgu.” Lokman berkata lantas ketawa. Aku mencubit lengannya perlahan. “Perasan!”
“Eh, Lokman. Laki aku mana?” soal Ami sambil menoleh-noleh ke belakang. Mendengar pertanyaan Ami, Lokman terus menekup bibirnya.
“Alamak, laki kau tertinggal kat… luar bilik guru. Hehe. Si Fatih tu ada kat luar, katanya segan nak masuk dalam. Pergilah tengok.” Ami pantas meminta diri, mahu menjenguk keadaan suaminya di luar bilik guru.
“Ariesa, berapa bulan dah?” Pertanyaan Puan Waheeda mematikan ketawaku. Alamak, mana cikgu tahu ni?
“Berapa bulan apa ni cikgu?” Aku pura-pura tidak tahu. Bibir Puan Waheeda terus memuncung, menunjukkan ke arah perutku.
“Itu hah, kandungan kamu tu dah berapa bulan?” Puan Waheeda berkata. Aku sudah mulai menggosok belakang kepalaku perlahan sambil memaparkan sengihan kepada guru Matematik itu.
“Ala, ingat pakai baju besar-besar bolehlah saya sorok. Dah lima bulan cikgu.” Aku menjelaskan sambil mengusap perutku lembut. Lokman sudah mulai tergelak besar.
“Itulah, abang dah cakap. Mesti orang perasan jugak. Tak percaya cakap abang.” Aku menjeling suamiku manja. Ah, geramnya aku.
“Dahlah, gaduh pulak nanti. Itulah Ariesa, kononnya nak sorok daripada cikgu ya? Dah lima bulan mana boleh sorok lagi. Ish kamu ni, macam tak pernah mengandung.” Puan Waheeda mulai membebel. Aku hanya tersengih nakal.
“Adik Faqih!” jerit Aazad lantas berjalan ke arah putera sulung Ami yang muda beberapa bulan daripadanya. Ami yang sedang memimpin Faqih tersenyum melihat gelagat Aazad. Kelihatan di belakang Ami, suaminya Fatih sedang menggalas beg besar. Mungkin itu barang keperluan Faqih.
“Cikgu! Inilah suami saya, Fatih. Tadi segan nak masuk dalam. Punyalah susah saya nak pujuk dia.” Ami turut mahu memberitahu Puan Waheeda bahawa dia juga telah bersuami. Faqih pantas didukungnya sementara Aazad sudah terjengket-jengket mahu mencapai tangan Faqih.
Aku tersengih melihat gelagat Aazad lalu mendukung anak kecil itu. Pipi montelnya aku cium perlahan. Lokman tersenyum melihatku lantas merangkul erat pinggangku. Tangan kanannya mengusap perutku perlahan.
“Sayang, terima kasih untuk baby girl ni. I love you..” Lokman berbisik ke telingaku. Aku tersenyum meleret sehingga ke telinga. Sementara tangan kananku mendukung Aazad, sebelah tanganku merayap ke pipinya lantas dicubit perlahan.
“I love you too.” Lokman tersenyum manis, jauh lebih manis daripada gula.
Dahulu, senyumannya itulah yang paling aku nanti dan rindu. Kini, senyuman itu datang sendiri kepadaku seakan memahami bahawa aku memerlukan sinaran senyumannya tanpa perlu mengungkap dengan kata-kata. Terima kasih Tuhan, kerana memberi aku cinta dan anugerah terbesar dalam hidup aku.
TAMAT
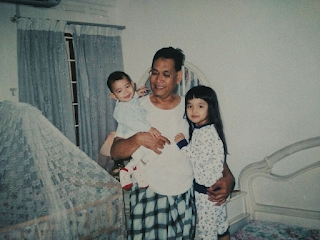
Comments
Post a Comment